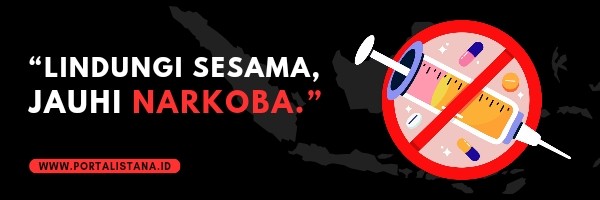Oleh: M. Fuad Nasar (mantan Sesditjen Bimas Islam. Saat ini Kepala Biro UIN Imam Bonjol Padang).
Semenjak dua dekade terakhir, transformasi pengelolaan zakat mewarnai dinamika kehidupan beragama di Tanah Air. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak memiliki potensi pengelolaan zakat yang besar, yaitu Rp 327 triliun dan baru terealisasi pengumpulan zakat secara nasional tahun 2023 sekitar Rp 32 triliun.
Blueprint Rencana Aksi dan Tahapan Pengembangan Pengelolaan Zakat Indonesia 2025 – 2045 tertuang dalam Peta Jalan Zakat Indonesia 2045. Buku roadmap zakat berbasis data yang disusun oleh BAZNAS bekerja sama dengan Kementerian Agama diluncurkan pada 20 Desember 2024.
Peta Jalan Zakat Indonesia memuat gambaran evaluatif tentang apa yang telah dilakukan dan arah kebijakan ke depan oleh segenap entitas pemangku kepentingan perzakatan guna mencapai visi pengelolaan zakat 2045 yakni, “Era Keemasan Zakat Indonesia”.
Transformasi, inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan zakat adalah suatu keniscayaan, namun semua itu harus berpegang pada tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada beberapa kesempatan, saya kerap mengutarakan bahwa undang-undang zakat maupun wakaf berfungsi bukan sekadar mengatur tata kelola, tetapi sekaligus mengakselerasi zakat dan wakaf yang lebih maju dan memberi manfaat optimal kepada umat secara lebih luas.
Secara substansial zakat bukan sekadar menyisihkan 2,5 persen dari harta dan hasil usaha untuk disalurkan kepada mustahik delapan asnaf yang dari sisi nominalnya lebih kecil daripada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Zakat adalah rukun Islam yang mendeklarasikan bahwa harta mempunyai fungsi sosial. Dalam harta yang telah mencapai nisab (batas wajib zakat) terdapat bagian tertentu hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta (mal) dan hasil usaha (kasab). Harta kekayaan tidak seyogianya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja agar tidak terjadi kemiskinan ekstrem di masyarakat.
Islam mengajarkan zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yakni ibadah dengan harta yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan. Zakat sebagai subsistem ekonomi syariah bukan ciptaan manusia, melainkan syariat Ilahiah. Petugas zakat yaitu amil adalah profesi yang disebut Tuhan dalam Al-Quran. Peran para amil yang ikhlas, adil dan ihsan menjadikan zakat berdaya untuk mendekatkan jarak si kaya dan si miskin.
Gerakan zakat adalah aksi kolektif umat Islam untuk melawan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial. Zakat bukan charity atau belas kasihan orang kaya kepada orang miskin, tetapi merefleksikan tanggungjawab sosial yang sifatnya wajib dalam agama. Dalam konteks ini para ahli memiliki keleluasaan untuk menjabarkan zakat dari perspektif ekonomi dan mengembangkan ekonomi menggunakan perspektif zakat. Sistem redistribusi harta melalui instrumen zakat menurut teori ekonomi akan meningkatkan konsumsi dan daya beli dalam suatu mata-rantai perekonomian yang berkelanjutan.
Seorang ahli ekonomi Barat yakni Prof. Neal Robinson, Guru Besar University of Leeds United Kingdom (UK) menulis, “Zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubung dengan adanya larangan riba, zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta, namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan.”
Dalam Al-Quran (Q.S. Ar-Rum [30]: 39) secara sosio ekonomi diungkapkan perbandingan antara riba dan zakat. Zakat menumbuhkan harta dan kesejahteraan serta pemerataan, sedangkan riba menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan kemanusiaan. Orang yang beriman kepada Tuhan semestinya menjauhi praktik riba dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi riba bertentangan dengan sunnatullah dan Pancasila yang ditolak oleh semua agama. Praktik riba maupun judi menghalangi investasi, mematikan semangat berbagi dan memberi. Penimbunan harta, riba dan judi diharamkan karena merusak dan meracuni perekonomian. Sedangkan zakat bertujuan untuk mendorong kegiatan memproduktifkan harta dan mengembangkan semangat tolong-menolong (ta’awun, takaful) antarsesama.
Pengaturan tata kelola zakat dengan perundang-undangan menegaskan bahwa Republik Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara berketuhanan. Cendekiawan internasional alm Dr. Soejatmoko (1922 – 1989) mengatakan agama adalah bahasa yang tidak bisa dan tidak mungkin dihapus dari perbincangan perkembangan kebudayaan masyarakat di Asia. Pandangan mantan Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tokyo itu relevan diketengahkan kembali di era kebangkitan ekonomi umat dengan inspirasi nilai-nilai agama.
Pandangan Soejatmoko sejalan dengan perspektif Islam bahwa ekonomi tak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam maupun kebijakan ekonomi ekstraktif (pemerasan dan anti lingkungan) hingga menimbulkan kemudaratan di muka bumi harus dihindari.
Masalah ekonomi hampir selalu beririsan dengan masalah non-ekonomi, seperti keadilan, penegakan hukum, etika-moral, dan keberpihakan kepada kaum lemah yang merupakan nilai-nilai agama dan tidak ditemukan dalam kamus ekonomi konvensional. Kemiskinan, dampak konflik, bencana, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial tidak dapat dipandang sebagai masalah sekuler yang berada di luar radar kepentingan agama untuk mengatasinya.
Dalam waktu belakangan disadari bahwa zakat dan wakaf sebagai elemen ekonomi syariah menjadi jaring pengaman sosial di era disrupsi ekonomi neokapitalis. Ekonomi syariah yang berkembang di tataran gobal dan nasional sejauh ini mencakup dua sektor atau elemen yaitu:
Pertama, sektor keuangan komersial, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, industri halal, dan industri keuangan non-bank syariah. Kedua, sektor keuangan sosial, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Penguatan keuangan sosial syariah di negara kita melibatkan berbagai stakeholder dan terhubung dalam suatu ekosistem yang inklusif. Di samping peran Kementerian Agama, patut diapresiasi dukungan institusi yang mengawal stabilitas keuangan, sistem pembayaran dan moneter dalam hal ini Bank Indonesia.
Para kolega di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, sebagaimana saya mengetahui ketika sekian lama pernah berinteraksi dan bekerja sama turut berperan dalam mendorong penguatan literasi dan tata kelola zakat dan wakaf. Para pengambil kebijakan di Bank Sentral menyadari bahwa stabilitas moneter dan keuangan tidak cukup ditopang hanya oleh sektor keuangan komersial saja, tetapi memerlukan dukungan sektor keuangan sosial. Selain itu juga peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mengoordinasikan dan mengakselerasi kontribusi ekonomi syariah khususnya termasuk zakat dan wakaf.
Dalam kaidah umum, pertumbuhan ekonomi dipandang baik kalau tidak melahirkan ketimpangan golongan kaya dan miskin, apalagi membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Sebuah agenda besar ke depan adalah mengkapitalisasi peran zakat terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi.
Setelah sekian dekade umat menyemai gerakan zakat, insya allah esok lusa diharapkan menuai kesejahteraan umum. Peran dan kontribusi zakat diharapkan lebih dari sekadar pendekatan adaptif terhadap isu-isu tren dunia. Pergerakan zakat Indonesia perlu secara konsisten mengedepankan gagasan-gagasan orisinil sebagai kontribusi umat terhadap pembangunan berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.
Peran amil sebagai ujung tombak pengelolaan zakat bukan hanya sekadar mengamalkan pengetahuan dan kompetensinya semata, tetapi amil haruslah memberikan hatinya untuk gerakan zakat. Sisi humanis dari gerakan zakat tidak boleh diabaikan yaitu peduli dan memuliakan kaum mustad’afin serta orang-orang yang terpinggirkan dalam persaingan hidup. Amil zakat – menurut istilah Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA – haruslah menjadi “sahabat spiritual umat”.
Sesama organisasi pengelolaan zakat perlu saling mendukung dengan rencana kerja yang terintegrasi. Semangat kolaborasi dalam lingkungan yang harmonis perlu diperkuat di tengah perkembangan pengelolaan zakat yang semakin dinamis dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Amil zakat yang hebat adalah yang senantiasa dekat dengan persoalan-persoalan riil kemiskinan/kemanusiaan dan berguru pada realitas. Saya membayangkan adakalanya amil zakat bekerja dalam keramaian dan ada waktunya amil bekerja dalam sunyi.
Menyemai gerakan zakat untuk Indonesia Maju dan mempersiapkan Era Keemasan Zakat Indonesia 2045 pada hakikatnya adalah kerja untuk turut mewujudkan tujuan bernegara dan memperkokoh sendi-sendi senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan cita-cita akhir Indonesia yang adil dan makmur. Pengelolaan zakat Indonesia dahulu, sekarang dan mendatang menuju kepada tujuan yang ideal tersebut.